Obscura
Cairan bening di hadapanku berputar perlahan. Meliuk, menyapu lembut tepian
gelas dan meninggalkan jejaknya dalam bentuk mutiara. Untuk sesaat aku sempat
merasa gelombang-gelombang tersebut seolah berpadu selaras dengan hentakan
suara yang keluar dari sudut-sudut ruangan. Pada satu waktu mereka seperti
sepucuk selendang yang berkelebat liar diterpa angin kencang. Di waktu lain
mereka mendesah, membelai lidah dan dinding leherku dengan satu gerakan
sensual. Tetapi aku lebih sering melihat mereka terdiam, hanya bergetar
perlahan karena manusia-manusia di sekelilingku tidak bisa diam. Sibuk
menciptakan kesenangan dalam kungkungan gelembung privasi masing-masing.
Sama seperti diriku.
Semakin lama aku terdiam, ada satu rasa di dalam rongga dadaku yang memberontak. Bila perlu ia bisa saja membuka jalannya melalui rusuk-rusukku. Saat itulah aku memindahkan tepi gelas ke bibirku. Kutenggak habis cairan tersebut hingga membilas basah rasa jahanam yang ingin membebaskan dirinya itu.
Aku ingin melihatmu.
Kepalaku berdenyut. Barulah aku sadar aku telah mengulangi siklus tersebut untuk yang keempat kalinya. Aku mengalihkan pandanganku kepada manusia-manusia di lantai dansa. Di bawah cahaya magenta yang suram, aku hanya dapat mengamati tubuh-tubuh yang bergerak liar bagaikan riak di bawah hantaman dayung. Sama sekali tak menarik. Tidak seperti gelombang-gelombang yang tadi menemaniku.
Tiba-tiba ada sesuatu yang memaksa pandangan mataku untuk kembali fokus. Seorang wanita, kutaksir usianya lebih dari dua puluh tahun, meliukkan pinggulnya di hadapan seorang pemuda yang tampak sedikit lebih muda. Gaunnya yang gemerlap melekat di tubuhnya seolah itulah kulit keduanya. Ujung gaunnya mengibas mengikuti gerak pinggulnya yang binal, rambutnya tergerai membelai punggungnya yang terbuka. Pemuda yang menjadi pasangan dansa liarnya memakai kemeja hitam pas badan, mengaksentuasi semua lekukan di tubuhnya.
Kuamati mereka untuk beberapa saat. Perlahan, tanganku merogoh kamera digital yang terselip di saku celana. Kurasakan ujung lidahku membelai gigi taring. Rasa sesak itu kembali.
Sudah lama aku menunggu kehadiran mereka.
* * *
Anton meletakkan lembaran file itu ke atas mejaku dengan serampangan.
“Targetmu malam ini. Eden, jam 11, ground floor”.
Ada foto seorang wanita yang terpampang di bagian depan berkas-berkas tersebut. Wajahnya tirus, namun masih terlihat menawan. Ia mengenakan busana formal layaknya pekerja kantoran. Kuangkat pandanganku ke Anton.
“Boleh aku menebak? Penggelapan uang lagi?”
“Lebih dari yang kau bayangkan. Klien kita minta wanita ini terpampang di headline koran-koran besar dengan judul Istri Simpanan Bupati D Terbukti Berselingkuh, sub-judul, Bukti Retaknya Keluarga Terkaya Di Nusantara”. Tangan Anton bergerak mendramatisir setiap ucapannya.
“Kamu terbalik meletakkan judul dan sub-judulnya. Meskipun begitu, idemu itu cuma cocok untuk tabloid-tabloid pinggir jalan yang menjual bualan saja”.
“Kok sepertinya kamu lupa dengan filsafat perusahaan, sih? Kita juga menampilkan bualan. Bualan yang nyata dan bisa menentukan nasib satu negara”.
Aku tersenyum kecil. “Lucu juga, Ton, membayangkan sebuah peradaban besar bisa menjadi puing dalam sekejab hanya karena gunjingan yang terlanjur meluas. Yang digunjingkan bukan hal yang kecil pula. Komponen-komponen penggerak dan pengatur laju masyarakat! Penentu arah gerak negara! Dan yang membuatnya selip dari jalurnya hanyalah kerikil-kerikil kecil yang terlanjur menumpuk karena lupa disapu”.
“Seandainya ada yang menyapu, pasti tidak akan selip” Anton menimpali. “Penyebab kerikil itu menumpuk tak lain karena ada yang memang suka menumpuk kerikil di atas rel demi sebuah kepuasan semu. Tak ada yang salah dengan kerikil itu sendiri”.
Kami berdua tergelak. Kuseka sedikit air mata di ujung kelopak mataku. “Jadi, inikah bakal kerikil baru yang akan kita ciptakan?”
“Renda sudah menyiapkan kolom khusus di laman Sassus. BISIKAN akan ramai dua detik setelah foto-fotomu selesai di-upload”.
* * *
Apakah yang sebenarnya kulihat melalui layar bidik? Bukan, apa yang sebenarnya kucari saat kuarahkan pandangan ini kepadamu?
Jauh sebelum aku bekerja untuk Anton, kulewatkan hari-hariku sebagai fotografer untuk sebuah majalah mode. Kuresapi detik demi detik mencari setiap sudut dan sisi dari para model. Setiap hal yang menonjolkan keanggunan, kemewahan, hidup yang sempurna. Kurangkum semuanya dalam satu bidikan jitu dan bunyi mekanis yang mengikuti sesudahnya.
Pada masa inilah aku dipertemukan kepadanya.
Agensi modeling yang membawahi Ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa aku sangat beruntung bisa mengabadikan dirinya. Kebanyakan model yang aku temui memang rupawan, namun aku tak dapat melihat jiwa mereka di atas kertas. Tidak dengan Ia. Saat kami berjabat tangan, ada sesuatu yang menembus rongga kepalaku. Ada jiwa yang meluap di balik gerak-geriknya yang tenang, dan aku merasa jiwa tersebut akan semakin menggelora setelah kuabadikan.
Tak pernah aku menjalani sesi pemotretan selancar ini. Ia mematuhi semua arahanku dan sanggup menampilkan apa yang aku kehendaki untuk ditampilkan. Pekerjaan kami selesai hampir satu jam lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan.
Waktu istirahat. Semua orang sudah keluar dari ruangan, aku tetap tinggal di balik komputer untuk memberikan beberapa sentuhan akhir pada hasil jepretanku. Aku tidak menyadari bahwa Ia masih ada di ruangan itu, kalau saja dia tidak mendadak berbicara.
“Apa yang kamu cari dari diriku?”
Aku tertegun, tak siap dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Ia menuang anggur ke dalam sebuah gelas tinggi. Diputarnya gelas itu perlahan sebelum menyesap sedikit. Cairan merah itu bergolak menyapu bibirnya. Ia memandangiku lekat-lekat. Ia tahu aku tak mampu menjawab. Sebuah senyum merekah di bibirnya. Setengah mengejek, setengah kemenangan. “Aku bertemu seorang bodoh lagi”.
Nafasku sesak. Ada rasa yang tiba-tiba menghimpit dadaku. Tak bisa kulepaskan pandanganku darinya saat dia meletakkan gelasnya di atas meja dan berjalan ke arahku. Tidak, pandanganku telah diikat oleh matanya. Matanya yang tajam menusuk.
Ia merendahkan tubuhnya hingga wajah kami sejajar. Senyum itu tetap ada. Ia berkata, “Semua orang menginginkan aku”.
“Bukankah itu sudah jelas?” Bibirku bergerak sendiri. “Engkau sempurna. Selama aku menjalani karirku ini aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang mampu menampilkan jiwanya seperti kamu”.
“Bukan itu saja yang mereka inginkan” Ia mendekatkan bibirnya ke kupingku. Nafasnya menyapu kulitku, mengirimkan getaran ganjil yang membuat dadaku semakin sesak. “Mereka menginginkan aku seutuhnya. Mereka ingin hidupku, mereka ingin jiwaku”.
“Mengapa mereka ingin memiliki jiwamu?”
“Sebab hidup mereka tidak akan berarti tanpa diriku. Aku tidak memilih untuk menjadi pelipur lara mereka, tak peduli mereka memang sedang berduka atau terus berputar dalam lingkaran pikirannya saja. Mereka yang mencariku, mereka terus memikirkanku, mengulang-ulang namaku dalam setiap kata. Seperti penolak bala. Membuatku muak”.
“Apa yang harus kulakukan?”
Keheningan meliputi kami. Ia mengambil kameraku dari sisi komputer dan meletak-kannya di telapak tanganku.
“Hancurkan aku”
Lalu bibirnya melekat pada bibirku. Lalu semua bergerak bagaikan mimpi paling absurd. Satu waktu kesadaranku kembali dan kudapati diriku berlutut di atasnya. Wajahnya memenuhi jendela bidik, seolah dia hidup dan bernafas di sana. Senyumnya merekah lebar, mempertunjukkan taringnya. Merah membasahi rambutnya, tubuhnya.
Sesak di dada ini menjadi tak terkendali. Sejenak, sebelum kesadaranku memudar, kurasakan ujung lidahku menyapu taringku. Mungkin ini yang kulihat darinya. Detik-detik musnahnya suatu keindahan yang diagungkan. Dan aku menikmati setiap geliat, setiap desah yang Ia keluarkan saat nyawanya meregang dalam lensa.
Setelah itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Semenjak kejadian itu, aku seolah tak mampu lagi untuk bekerja seperti dulu. Kuputuskan untuk mengundurkan diri dan berfikir untuk menjadi freelancer. Saat itulah Anton datang dan menawarkan jalan keluar.
“Apakah kamu menyukai keindahan?” Dia bertanya sembari melihat-lihat berkas foto di komputerku. Pandangannya terpaku pada Ia. “Semua orang menyukai keindahan. Semua orang mencari keindahan dalam keseharian yang semakin banal. Mereka terus membicarakannya, menggunjingnya, mencoba mengabadikannya dalam lisan. Yang tidak mereka ketahui adalah semakin jauh gunjingan mereka, keindahan itu akan makin menjadi, namun ia sudah jauh tercerabut dari akarnya. Yang menunggu di hadapannya adalah kehancuran, muspra”.
Anton menunjuk foto di hadapanku. “Dia adalah contoh keindahan yang harus muspra di tangan pergunjingan. Aku yakin kamu telah menyadarinya”.
“Ia musnah di tanganku”.
“Keputusannya tepat. Ia memilih gugur ketimbang terus memupuk kebusukan. Sayangnya, tak banyak orang-orang seperti itu di dunia ini. Hanya menambah beban yang tak perlu saja. Mereka cuma bisa jatuh setelah pijakan mereka dihantam batu berkali-kali. Nah, kulihat kamu sedang membutuhkan pekerjaan. Maukah kamu bergabung denganku?”
“Apa yang bisa kuharapkan darimu?”
Satu sudut di bibir Anton terangkat. “Dari segi finansial, tak banyak. Aku tahu kamu bukan tipe yang gila harta. Aku menawarkan apa yang kamu cari. Ekstase dari pandangan. Detik-detik hancurnya keindahan dan kesempurnaan”.
* * *
BISIKAN. Suatu sudut di dunia maya yang menawarkan segala yang tak nampak di media-media awam. Mereka yang terkenal, mereka yang multijutawan, mereka yang sanggup menggerakkan naluri dasar setiap orang untuk membicarakan dirinya. Mereka yang tidak sadar bahwa sebentar lagi mereka akan bergerak menuju kejatuhan hanya karena selembar citra mereka terpampang jelas bagi semua. Sekilas kelihatan seperti kolom gosip murahan. Tapi Anton menambahkan bahwa semua foto itu adalah hasil pesanan.
“Intinya, kita dibayar untuk menjatuhkan pribadi seseorang yang sudah dikenal publik melalui publik juga. Bedanya, kita bekerja secara anonim. Jangan kuatir, aku punya banyak kenalan yang juga bekerja di media-media ibukota. Mereka tidak akan membocorkan rahasia kita”.
“Jadi seperti kasus video-video tak senonoh itu? Semula masyarakat tidak tahu, lalu karena ulah satu orang tak bernama beritanya bisa dibahas satu bulan lebih? Kemudian ada kabar burung bahwa seseorang memang menginginkan hal itu terjadi?”
“Seperti itu. Aku sengaja memilih format foto karena kecepatan dan keakuratan daya tangkap yang ditawarkan kamera digital. Itu saja belum cukup jika kita ingin hasil bidikan kita tidak terlihat amatiran”.
“Makanya kamu langsung mengincarku, Ton? Pintar”.
“Yah, siapa tahu kamu bisa bertemu dengan Ia lagi. Siapa tahu. Dia kini sudah melebur dalam keramaian, tak lagi diletakkan di atas altar seperti dulu, tapi aku yakin kamu masih bisa mengenalinya seperti saat sebelum dia berubah. Walaupun hanya berupa sepotong wajah tak dikenal di dalam fotomu”.
Aku menelan ludah. Anton meletakkan tangannya di pundakku. “Gairahmu, ekstasemu saat melihat mereka yang bergelimang kesempurnaan perlahan menguap, Ia yang membangkitkan rasa itu dalam dirimu. Rasa itu pula yang membuatmu memilih untuk bekerja denganku. Tak ada yang salah. Aku hanya meminta kesanggupanmu untuk menghadapi segala resikonya”.
Anton, kamu tak perlu menunggu jawabannya terlalu lama.
* * *
Cahaya magenta mengguyur tubuh pasangan tersebut. Menyelimuti setiap ceruk dan lekuk dengan merah. Mereka lengah. Tak menyadari keduanya masuk dalam bidikanku. Jantungku berdetak, mengembalikan rasa sesak yang kukenal ke dalam rongga dada.
Dari balik keramaian, Ia perlahan hadir. Memandangku. Masih dengan senyum itu.
Telunjukku menekan tombol pemantik. Cahaya, lalu denting mekanik.
Karya :
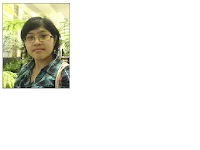 Namanya Nasti Mudita. Ia dilahirkan di Malang 23 tahun yang
lalu pada tanggal sembilan, bulan tujuh. Sempat yakin dirinya Bonek tulen
karena masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di Surabaya sampai dia menginjak
kelas 5 SD dan harus kembali lagi ke kota kelahirannya. Mengakui diri sendiri
sebagai pop culture junkie –
anak-anak yang menonton lebih banyak film Hollywood dan animasi Jepang
ketimbang sinetron, apalagi ludruk. Bakat menulisnya ia temukan secara tidak
sengaja. Ia bertekad akan menjadikan bakat ini sebagai pekerjaan utamanya dan
berusaha untuk memperbaiki produktivitasnya yang kadang angin-anginan.
Namanya Nasti Mudita. Ia dilahirkan di Malang 23 tahun yang
lalu pada tanggal sembilan, bulan tujuh. Sempat yakin dirinya Bonek tulen
karena masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di Surabaya sampai dia menginjak
kelas 5 SD dan harus kembali lagi ke kota kelahirannya. Mengakui diri sendiri
sebagai pop culture junkie –
anak-anak yang menonton lebih banyak film Hollywood dan animasi Jepang
ketimbang sinetron, apalagi ludruk. Bakat menulisnya ia temukan secara tidak
sengaja. Ia bertekad akan menjadikan bakat ini sebagai pekerjaan utamanya dan
berusaha untuk memperbaiki produktivitasnya yang kadang angin-anginan. 
Komentar
Posting Komentar